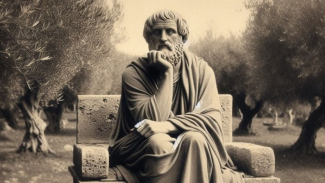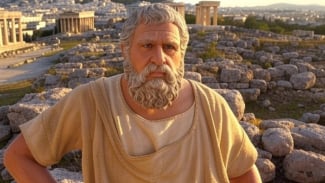Pernikahan, Poligami, dan Patah Hati: Kritik Kartini terhadap Budaya Patriarki Jawa
- Bicara Tokoh
Jepara, WISATA – Tulisan ini disusun berdasarkan esai kenangan pribadi karya Marie Ovink‑Soer tentang Raden Adjeng Kartini, tokoh emansipasi perempuan Jawa. Marie Ovink‑Soer adalah seorang wanita Belanda yang mengenal Kartini secara dekat ketika tinggal di Jepara. Dalam tulisannya, Marie menceritakan pengalaman pribadi, pengamatan, dan interaksinya selama tujuh tahun bersama Kartini dan keluarganya, yang memberi gambaran mendalam tentang pemikiran, perjuangan, dan karakter Kartini dalam konteks budaya Jawa kala itu. Artikel ini merupakan bagian keempat dari rangkaian sepuluh seri berita bersambung.
Bayang–Bayang Pernikahan Terpimpin dalam Tradisi Adat Jawa
Sejak kecil, Kartini memahami bahwa dalam budaya Jawa kolosal, pernikahan bukan urusan hati, melainkan urusan keluarga besar. Ia menyaksikan gadis priyayi dijodohkan sesuai kriteria sosial: status, kekayaan, dan ikatan antar-klan. Tanpa pernah bertatap muka dengan calon suami, seorang gadis Jawa harus mengucap “ya” atau “tidak” berdasarkan nama, silsilah, dan janji yang diwakilkan oleh orang tua.
“Kami bahkan tidak melihat wajah calon suami,” tulis Kartini dalam salah satu suratnya. “Bagaimana mungkin cinta tumbuh, apabila pertemuan dan pengenalan saja dilarang adat?”
Tekanan adat tersebut jauh lebih berat daripada sekadar ikatan janji. Bagi banyak keluarga priyayi, pernikahan adalah alat politik kecil: memperkuat aliansi, menjaga wibawa, dan menegakkan hierarki sosial. Di tengah kerumitan adat itu, Kartini tumbuh dengan rasa gelisah, menolak ide bahwa perempuan harus pasif dan patuh tanpa mempertanyakan makna cinta.
“Poligami Biasa, Perempuan Terpinggir”
Kartini tak hanya menentang konsep perjodohan terpimpin; ia juga muak dengan praktik poligami yang lazim di kalangan bangsawan Jawa—laki‑laki boleh beristri hingga empat, sementara perempuan tak punya hak setara. Lewat surat-suratnya, Kartini mengecam keras:
1. Kepemilikan atas tubuh perempuan. “Perempuan dianggap milik suami,” tulisnya. “Padahal tubuh dan hati kami milik kami sendiri.”
2. Rasa takut dan patah hati. Banyak perempuan yang hidupnya tercerai-berai, patah hati ketika “istri kedua” hadir, meminggirkan istri pertama.