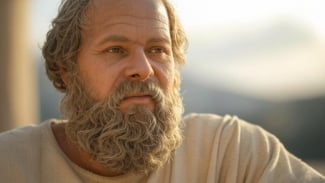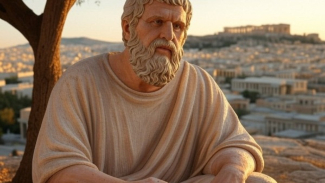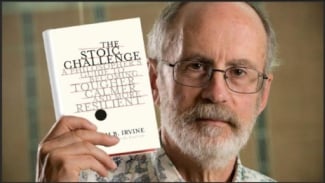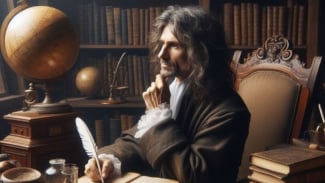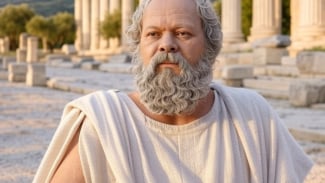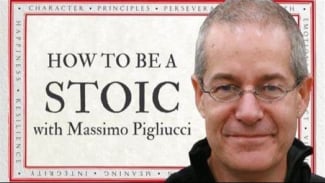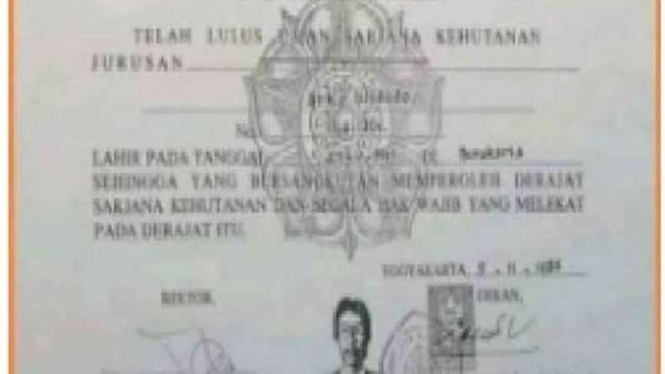Membandingkan Pemikiran Descartes dan Al-Farabi: Rasionalitas, Ketuhanan, dan Tujuan Filsafat
- Image Creator Grok/Handoko
Membandingkan Pemikiran Descartes dan Al-Farabi: Rasionalitas, Ketuhanan, dan Tujuan Filsafat
Malang, WISATA - Dalam bentangan sejarah filsafat dunia, dua tokoh dari dua dunia yang berbeda muncul sebagai pemikir besar yang mendefinisikan ulang makna keberadaan dan peran akal: René Descartes, filsuf Perancis dari abad ke-17, dan Al-Farabi, filsuf Muslim dari dunia Islam klasik pada abad ke-10. Meski lahir dalam latar budaya dan tradisi yang jauh berbeda, keduanya menyumbangkan pemikiran monumental yang hingga kini terus dibicarakan, dipelajari, dan dijadikan rujukan.
Descartes dikenal luas dengan semboyannya yang menggema dalam sejarah pemikiran: Cogito, ergo sum — Aku berpikir, maka aku ada. Pernyataan ini bukan hanya ekspresi keyakinan pribadi, melainkan juga deklarasi filsafat baru yang berangkat dari keraguan radikal terhadap semua hal yang tidak dapat dibuktikan secara rasional. Descartes memulai dari keraguan, dan dari titik itulah ia menemukan satu kepastian: bahwa dirinya berpikir. Dan karena berpikir tidak mungkin tanpa keberadaan, maka keberadaannya menjadi fakta pertama yang tak terbantahkan. Filsafat Descartes adalah filsafat yang menegaskan bahwa dasar dari segala pengetahuan adalah rasio manusia, dan dari sinilah bangunan ilmu pengetahuan harus dibangun.
Sementara itu, berabad-abad sebelum Descartes mengembangkan metode keraguan dan analisis rasionalnya, Al-Farabi telah membangun sistem filsafat yang memadukan warisan intelektual Yunani dengan prinsip-prinsip Islam. Al-Farabi, yang dijuluki “Guru Kedua” setelah Aristoteles, menempatkan akal sebagai pusat dari segala upaya manusia dalam mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan. Bagi Al-Farabi, filsafat bukan hanya untuk mengetahui, melainkan untuk mengubah jiwa dan masyarakat, mengarahkannya kepada kesempurnaan etis dan spiritual.
Jika Descartes menempatkan Tuhan sebagai penjamin kebenaran — karena menurutnya, pikiran kita bisa dipercaya hanya jika Tuhan yang Mahasempurna tidak menipu kita — maka Al-Farabi meletakkan Tuhan sebagai sumber eksistensi. Bagi Descartes, keyakinan akan Tuhan dibutuhkan agar manusia bisa yakin bahwa pikirannya bukan ilusi. Tapi bagi Al-Farabi, Tuhan adalah wujud pertama (al-mawjud al-awwal), dari mana semua realitas memancar. Di sini kita melihat perbedaan mendasar: Tuhan bagi Descartes berperan dalam dimensi epistemologis, sementara bagi Al-Farabi, Tuhan berfungsi ontologis sekaligus kosmologis.
Filsafat Descartes adalah filsafat individual, yang membentuk subjek sebagai pusat pengetahuan. Rasionalitas bersifat personal dan menjadi fondasi dari semua klaim kebenaran. Namun Al-Farabi menekankan bahwa puncak kebahagiaan manusia hanya bisa dicapai dalam struktur sosial-politik yang ideal, yang ia namakan Al-Madina Al-Fadila atau “Negara Utama”. Dalam negara ini, pemimpin adalah sosok bijak, seorang filsuf yang memiliki pengetahuan tertinggi tentang Tuhan dan realitas. Maka filsafat dalam pandangan Al-Farabi tidak hanya membebaskan individu, tetapi juga memandu tatanan sosial ke arah yang adil, rasional, dan spiritual.
Perbedaan keduanya juga tampak dalam pendekatan mereka terhadap metode berpikir. Descartes membongkar semua hal yang sudah mapan, lalu membangunnya kembali secara logis dari dasar yang paling pasti. Ia mencurigai pancaindra, meragukan pengalaman, dan hanya mempercayai apa yang bisa diuji oleh akal yang jernih. Sementara Al-Farabi membangun filsafatnya dari tradisi besar sebelumnya — terutama Aristoteles dan Plotinus — dan menyusunnya dalam sintesis besar dengan Islam, menciptakan sebuah sistem pemikiran yang komprehensif, meliputi metafisika, logika, etika, hingga teori politik dan musik.