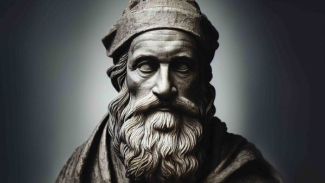Albert Camus: “When the Soul Suffers Too Much, It Develops a Taste for Misfortune”
- Cuplikan layar
"When the soul suffers too much, it develops a taste for misfortune."
– Albert Camus
Jakarta, WISATA - Apa yang terjadi ketika jiwa manusia terlalu sering disakiti? Mengapa ada orang yang tampak “terbiasa menderita,” bahkan seolah mulai mencari atau menikmati penderitaan itu sendiri? Albert Camus, filsuf Prancis yang dikenal karena pemikirannya tentang absurditas dan eksistensi manusia, memberikan pandangan yang tajam dan mengejutkan: jiwa yang terlalu sering menderita bisa mengembangkan rasa suka terhadap kemalangan.
Pernyataan Camus ini membuka ruang diskusi yang dalam. Tidak hanya soal rasa sakit dan penderitaan, tetapi juga bagaimana manusia — dengan segala kerentanannya — bisa terperangkap dalam pola rasa sakit yang berulang, dan pada titik tertentu, menemukan kenyamanan aneh dalam penderitaan itu sendiri.
Penderitaan sebagai Kebiasaan
Ketika seseorang menghadapi penderitaan terus-menerus, jiwa akan mencari cara bertahan. Dalam psikologi, ini disebut sebagai mekanisme adaptasi. Namun, terkadang mekanisme ini berkembang menjadi sesuatu yang lebih kompleks: rasa familiar terhadap penderitaan.
Penderitaan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu membuat seseorang merasa “aman” di dalam rasa sakit. Mereka tahu bagaimana rasanya dikhianati, ditinggalkan, gagal, atau merasa tidak berharga — dan karena itu, mereka tahu bagaimana bertahan. Sebaliknya, ketika kebahagiaan datang, mereka justru gelisah. Mereka merasa asing terhadap kedamaian, bahkan curiga akan datangnya malapetaka baru. Inilah yang dimaksud Camus dengan jiwa yang "mengembangkan selera terhadap kemalangan".
Menikmati Derita, Bukan Karena Masokisme
Perlu digarisbawahi bahwa “menikmati kemalangan” di sini bukanlah masokisme dalam arti klinis. Ini lebih kepada kondisi eksistensial — sebuah keterikatan emosional terhadap rasa sakit yang lahir dari pengulangan dan keterbiasaan. Jiwa tidak benar-benar senang menderita, tetapi ia merasa lebih aman dalam penderitaan karena itu adalah satu-satunya dunia yang ia kenal.
Albert Camus sendiri, dalam karya-karyanya seperti The Plague dan The Myth of Sisyphus, sering mengangkat tokoh-tokoh yang berada dalam penderitaan yang tidak masuk akal. Mereka tidak menyerah, tetapi juga tidak berharap. Mereka memilih untuk bertahan, bahkan ketika harapan tampak mustahil. Camus mengajak kita untuk menghadapi realitas sebagaimana adanya, termasuk penderitaan, tanpa berpura-pura atau melarikan diri.
Ketika Trauma Membentuk Pandangan Hidup
Orang yang pernah mengalami trauma berat — kehilangan orang tercinta, kekerasan masa kecil, pengkhianatan, atau kemiskinan ekstrem — sering membentuk lensa khusus dalam memandang hidup. Mereka cenderung melihat hidup sebagai rangkaian ujian dan ancaman. Bahkan saat segalanya berjalan baik, mereka merasa itu hanya sementara. Dalam diam, mereka menunggu luka berikutnya.
Fenomena ini menciptakan semacam keterikatan terhadap penderitaan. Bukannya ingin menderita, tetapi mereka merasa lebih siap menghadapinya daripada menikmati kebahagiaan yang rentan dan bisa sirna kapan saja. Jiwa yang terlalu sering disakiti akhirnya merasa “lebih nyaman” di dalam kegelapan, bukan karena ia menyukai kegelapan, tetapi karena terang terasa terlalu silau dan mengancam.
Dunia yang Tak Ramah dan Jiwa yang Bertahan
Camus menempatkan manusia dalam dunia yang sunyi dan tak peduli. Dunia tidak menawarkan makna, tetapi manusia tetap mencarinya. Dalam pencarian itu, penderitaan menjadi bagian tak terhindarkan. Tapi Camus tidak menyarankan kita menyerah. Sebaliknya, ia menantang kita untuk tetap memilih hidup, meskipun hidup itu sendiri penuh luka.
"Aku memberontak, maka aku ada," tulis Camus dalam The Rebel. Artinya, dalam penderitaan, manusia bisa menemukan kekuatan untuk melawan — bukan melawan takdir, tetapi melawan keputusasaan. Memilih untuk tetap manusia, tetap mencinta, tetap berharap, bahkan ketika semuanya tampak sia-sia.
Bagaimana Menyembuhkan Jiwa yang Terluka?
Pertanyaan besar yang muncul adalah: apakah jiwa yang telah mengembangkan selera terhadap kemalangan bisa sembuh? Jawabannya: bisa. Tapi butuh waktu, keberanian, dan terutama kesadaran. Menyembuhkan luka batin tidak berarti melupakan rasa sakit, tetapi belajar untuk tidak lagi melekat pada rasa sakit itu.
Langkah pertama adalah mengenali pola tersebut. Mengapa kita selalu kembali pada hubungan yang menyakitkan? Mengapa kita merasa tidak pantas bahagia? Mengapa kita merasa bersalah ketika hidup terasa tenang?
Setelah itu, kita bisa perlahan membentuk kebiasaan baru. Belajar menerima cinta tanpa rasa curiga. Belajar percaya bahwa hidup juga bisa memberi kehangatan. Belajar membiarkan diri sendiri bahagia — meskipun sesekali masih diselimuti keraguan.
Camus dan Harapan yang Keras Kepala
Meski banyak yang menganggap pemikiran Camus pesimistis, sesungguhnya ia adalah seorang optimis yang keras kepala. Ia percaya bahwa manusia bisa dan harus terus berjuang, meski dunia tidak memberi jaminan apa pun. Dalam penderitaan yang terus-menerus, manusia bisa memilih untuk tidak tunduk. Ia bisa memilih untuk bertahan — bahkan tersenyum di tengah kesakitan.
Camus tidak romantis terhadap penderitaan. Ia tidak memuliakannya, tetapi ia mengakuinya sebagai bagian dari kehidupan. Dan lebih dari itu, ia menyatakan bahwa kita tetap memiliki pilihan. Kita bisa tetap manusiawi, bahkan ketika dunia tidak.
Penutup: Melampaui Penderitaan
Jiwa manusia memang rapuh. Ia bisa hancur, retak, dan berubah bentuk oleh penderitaan. Tapi jiwa juga memiliki daya lenting luar biasa. Ia bisa sembuh. Ia bisa tumbuh. Ia bisa belajar mengenali keindahan tanpa rasa takut. Ia bisa mencintai kehidupan, bahkan setelah berkali-kali dikecewakan olehnya.
Pernyataan Albert Camus bukanlah ajakan untuk menikmati penderitaan. Tapi peringatan bahwa kita — sebagai manusia — rentan untuk terjebak dalam siklus rasa sakit. Dan hanya dengan kesadaran, kita bisa melampaui itu.
Karena pada akhirnya, hidup terlalu berharga untuk dihabiskan dalam luka yang sama.