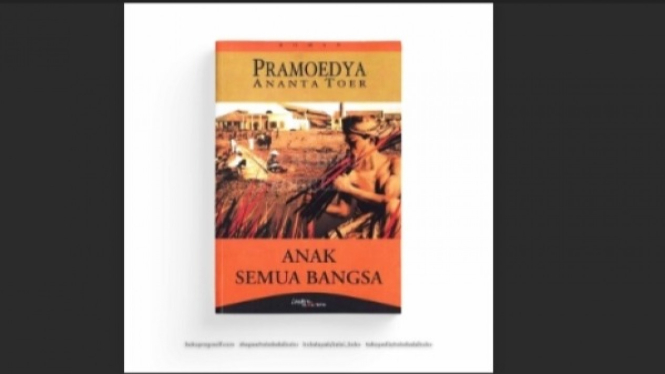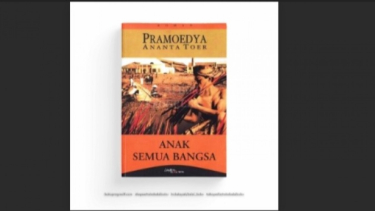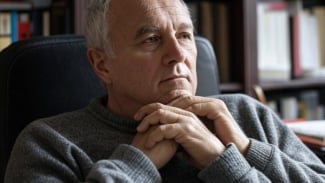Daftar Buku-Buku yang Dilarang Beredar Pemerintah Orde Baru dan Alasan di Baliknya
- Tangkapan Layar
Jakarta, WISATA - Selama masa Orde Baru di Indonesia (1966-1998), pemerintah yang dikendalikan oleh Presiden Soeharto menerapkan pembatasan ketat pada karya-karya sastra dan buku-buku yang dianggap bisa mengancam stabilitas politik. Banyak buku karya penulis terkenal dilarang beredar oleh Kejaksaan Agung atau lembaga lainnya, dengan dalih melindungi ideologi Pancasila dan menjaga keamanan nasional.
Tindakan ini berdampak besar pada kebebasan berekspresi dan budaya literasi di Indonesia. Buku-buku yang dilarang pada masa Orde Baru sering kali mengangkat isu-isu sensitif, termasuk perlawanan terhadap ketidakadilan sosial, sejarah pergerakan kemerdekaan, dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Berikut adalah beberapa buku terkenal yang dilarang, lengkap dengan alasan di balik pelarangannya:
1. Tetralogi Pulau Buru - Pramoedya Ananta Toer
Pramoedya Ananta Toer, seorang sastrawan besar Indonesia, menulis Tetralogi Pulau Buru yang terdiri dari Bumi Manusia (1980), Anak Semua Bangsa (1981), Jejak Langkah (1985), dan Rumah Kaca (1988). Buku-buku ini mengisahkan perjalanan Minke, seorang tokoh nasionalis di era kolonial, dalam mengejar keadilan. Namun, Tetralogi ini dilarang beredar karena dianggap mengandung ideologi Marxisme, yang dilarang keras pada masa itu. Larangan tersebut muncul karena Pramoedya pernah dituduh sebagai simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI), meski dirinya tidak pernah terlibat langsung.
2. Hoakiau di Indonesia - Pramoedya Ananta Toer
Selain Tetralogi Pulau Buru, karya Pramoedya lainnya, Hoakiau di Indonesia, yang menyoroti diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, juga masuk daftar buku terlarang pada tahun 1960-an. Buku ini mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak adil terhadap warga keturunan Tionghoa. Pada masa Orde Baru, sentimen anti-Tionghoa sangat tinggi, sehingga buku yang mengangkat topik ini dianggap mengancam keharmonisan sosial. Pelarangan buku ini mencerminkan sikap represif pemerintah Orde Baru terhadap isu-isu etnis yang dianggap sensitif.
3. Matinya Seorang Petani - Agam Wispi dan Penulis Lain
Matinya Seorang Petani adalah kumpulan puisi yang ditulis oleh Agam Wispi bersama beberapa penulis lain. Buku ini dianggap terlalu politis karena menggambarkan ketidakadilan sosial yang dialami oleh para petani. Tema perjuangan dan perlawanan terhadap ketidakadilan di kalangan petani membuat buku ini dicap subversif. Pelarangan ini mengindikasikan ketakutan pemerintah Orde Baru terhadap gagasan-gagasan yang mengancam stabilitas ekonomi berbasis agraris yang dijalankan oleh negara pada saat itu.
4. Wawancara Imajiner dengan Bung Karno - Christianto Wibisono
Buku Wawancara Imajiner dengan Bung Karno, karya Christianto Wibisono, diterbitkan pada 1977 dan langsung dilarang pada 1978. Buku ini menampilkan Soekarno, presiden pertama Indonesia, dalam wawancara imajiner yang mengkritik kondisi politik Indonesia di era Orde Baru. Soekarno, yang merupakan tokoh proklamator dan pemimpin revolusi, menjadi sosok simbol perlawanan terhadap Soeharto. Buku ini menggambarkan betapa Soekarno sebagai figur nasionalis memandang perkembangan politik yang terjadi setelah kemerdekaan dengan kritis, yang dianggap mengganggu pemerintah.
5. Indonesia di Bawah Sepatu Lars - Sukamdani Indro Tjahjono
Karya ini adalah pledoi dari Sukamdani Indro Tjahjono, seorang mahasiswa yang aktif dalam pergerakan mahasiswa. Indonesia di Bawah Sepatu Lars mengungkapkan pembelaan yang dilakukan mahasiswa terhadap militerisasi dan tindakan represif pemerintah Orde Baru. Buku ini dianggap subversif dan dilarang oleh pemerintah pada 1980 karena mengandung kritik tajam terhadap militer dan pengaruhnya dalam kehidupan politik Indonesia. Larangan ini mencerminkan sikap pemerintah yang menganggap kritik terhadap militer sebagai ancaman langsung.
Selama periode Orde Baru, ratusan judul buku dilarang beredar di Indonesia. Data resmi dari Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa antara tahun 1965 hingga 1998, sekitar 2.000 buku masuk dalam daftar hitam pemerintah. Berdasarkan data dari Lembaga Kebudayaan Nasional, sekitar 70% dari buku-buku yang dilarang mengandung unsur politik atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Selain itu, 20% buku dianggap mengandung subversi, sementara sisanya dianggap bisa mengganggu ketertiban umum.
Dampak Sosial dan Budaya
Pelarangan ini tidak hanya berdampak pada para penulis, tetapi juga pada masyarakat luas. Banyak pembaca kehilangan akses ke karya-karya kritis yang berisi pemikiran alternatif dan refleksi sejarah. Kebijakan sensor dan pelarangan buku ini menjadi penghalang dalam membangun budaya literasi dan kebebasan berpikir di Indonesia. Hingga hari ini, pelarangan tersebut dikenang sebagai salah satu bentuk represi yang paling kuat terhadap kebebasan berekspresi di tanah air.
Meski Orde Baru telah berakhir, dampaknya masih terasa dalam bentuk stigma dan ketakutan terhadap literatur yang mengangkat isu-isu kritis. Banyak di antara buku-buku yang dilarang di masa itu kini mulai diterbitkan kembali sebagai upaya untuk memulihkan literasi sejarah dan kebebasan intelektual masyarakat.
Upaya Pemulihan dan Literasi Sejarah
Saat ini, beberapa penerbit berusaha untuk menerbitkan ulang buku-buku yang dulu dilarang, dengan tujuan memperkenalkan kembali sejarah yang sempat terhapus. Generasi muda diharapkan bisa belajar dari sejarah kelam Orde Baru dan menghargai kebebasan intelektual serta hak berekspresi. Program pemerintah yang mendorong literasi sejarah melalui perpustakaan nasional dan arsip nasional juga turut berperan dalam melindungi warisan intelektual ini.